Saham ESG vs Konvensional: Mana yang Lebih Unggul?
- Apakah saham ESG benar-benar lebih unggul? Simak data kinerja, risiko, dan perbandingannya dengan saham konvensional.

Muhammad Imam Hatami
Author
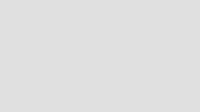

JAKARTA, TRENASIA.ID - Investasi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) makin di gandrungi pasar modal global maupun Indonesia. Aliran dana yang deras, regulasi yang semakin ketat, serta meningkatnya kesadaran investor terhadap isu keberlanjutan mendorong saham-saham berlabel “hijau” tampil impresif.
Di balik kinerja yang menjanjikan, muncul peringatan dari kalangan akademisi dan analis pasar, apakah ESG benar-benar didorong fundamental kuat, atau justru mulai memasuki fase “gelembung”?
Perbandingan kinerja antara saham berbasis ESG dan saham konvensional menunjukkan hasil yang tidak selalu seragam. Dikutip jurnal berjudul “ESG Investing: Evaluating the Financial Performance of Sustainable Portfolios,” mengungkap portofolio ESG mampu mengungguli saham konvensional dengan selisih rata-rata sekitar 4,3 persen per tahun.
Namun, temuan ini tidak bersifat universal. Analisis terhadap indeks global seperti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dan MSCI ESG Index periode 2010–2021 menunjukkan beberapa indeks ESG di Amerika Serikat dan Eropa mencatatkan kinerja sedikit lebih unggul dibandingkan indeks konvensional, sementara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika performanya cenderung setara atau sedikit tertinggal.
Dari sisi risiko, saham ESG secara umum dinilai memiliki volatilitas lebih rendah serta penurunan nilai (drawdown) yang lebih kecil saat pasar mengalami tekanan, sedangkan saham konvensional cenderung lebih fluktuatif, terutama pada periode krisis. Hal ini mengindikasikan bahwa keunggulan ESG sangat bergantung pada konteks waktu, wilayah, serta metodologi penelitian yang digunakan.
Sejumlah analis menilai keunggulan ESG sering kali didukung tata kelola yang lebih baik, mitigasi risiko operasional, serta reputasi perusahaan yang lebih kuat. Tetapi faktor aliran dana besar ke produk ESG juga dinilai turut mengerek harga sahamnya.
IDX ESG Leaders
Di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) aktif mengembangkan indeks berbasis keberlanjutan, salah satunya IDX ESG Leaders. Indeks ini berisi 30 emiten dengan penilaian ESG unggul, likuiditas tinggi, serta kinerja keuangan solid. Sepanjang 2025, IDX ESG Leaders mencatatkan kenaikan 8,49 persen dalam satu bulan terakhir (per Agustus) dan menguat 2,87 persen secara year-to-date.
Minat investor terhadap produk berbasis ESG juga meningkat. Total dana kelolaan (AUM) produk ESG di Indonesia mencapai Rp8,21 triliun. Saham-saham seperti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) menjadi pendorong penguatan indeks, terutama dari sektor teknologi dan energi terbarukan.
Komitmen regulator semakin jelas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI memperkuat standar pelaporan keberlanjutan. Sejak Januari 2025, BEI mengintegrasikan pelaporan ESG dalam sistem SPE-IDXnet dengan mengadopsi ASEAN Exchanges Common ESG Metrics. Hasilnya, sekitar 94 persen atau 882 emiten telah menerbitkan laporan keberlanjutan.
Selain itu, OJK menerbitkan SEOJK No. 25/SEOJK.04/2025 yang menetapkan porsi penjatahan IPO untuk investor ritel sebesar 50 persen. Kebijakan ini memperluas akses investor individu terhadap saham-saham potensial, termasuk yang berorientasi ESG. Regulator juga berencana menaikkan batas minimal free float dari 7,5 persen menjadi 15–20 persen guna meningkatkan likuiditas dan tata kelola perusahaan.
Risiko “ESG Bubble”
Di tengah optimisme tersebut, muncul peringatan mengenai potensi “ESG Bubble”. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika harga saham ESG melambung tinggi bukan karena fundamental yang solid, melainkan karena euforia dan aliran dana besar.
Penelitian dari Swiss Finance Institute (periode 2016–2021) menunjukkan, sebagian kinerja unggul ESG dipengaruhi oleh derasnya aliran dana global ke sektor ini. Ketika aliran dana tersebut melambat, risiko koreksi harga meningkat.
Selain itu, saham sektor energi terbarukan dan teknologi hijau kerap diperdagangkan pada valuasi tinggi, menyerupai pola gelembung dot-com awal 2000-an. Investor juga cenderung membayar “green premium”, yaitu harga lebih mahal untuk saham yang dianggap bermoral atau ramah lingkungan.
Risiko lain adalah praktik greenwashing, yakni klaim keberlanjutan yang dilebih-lebihkan. Jika terbukti tidak sesuai fakta, harga saham berpotensi terkoreksi tajam. Bagi investor ritel, ESG bukanlah jalan pintas menuju kekayaan instan. Pendekatan yang lebih bijak adalah memandang ESG sebagai kerangka seleksi perusahaan yang lebih sehat dan tangguh dalam jangka panjang.
Diversifikasi, analisis fundamental, serta pemahaman valuasi tetap menjadi kunci. Label “ESG” tidak otomatis menjamin imbal hasil superior. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya transparansi, prospek pasar ESG Indonesia memang cerah. Namun investor perlu waspada terhadap potensi volatilitas jika sentimen pasar berubah atau aliran modal asing keluar secara tiba-tiba.
Pada akhirnya, investasi ESG menghadirkan dualisme: peluang imbal hasil kompetitif dengan risiko relatif lebih terkendali, tetapi juga potensi gelembung jika euforia tak diimbangi analisis mendalam. Bagi investor yang cermat, ESG bisa menjadi “vitamin” untuk memperkuat portofolio, bukan sebagai “obat ajaib” yang menjamin keuntungan instan.

Ananda Astri Dianka
Editor
